| Written by Ibnu Faizal | |||

(Image Source: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8qdag76Qxegz_r9Q1y_OT7TkYFXAidhJ2-_KXx8Ivz5mtEPI8)
Sebuah
daerah tangkapan dapat digambarkan sebagai suatu wilayah daratan yang
dikelilingi oleh dataran yang lebih tinggi seperti perbukitan dan
pegunungan, di mana air mengalir ke titik terendah (misalnya sungai,
sungai, danau atau laut). Sebuah daerah tangkapan besar sering terdiri
dari sejumlah tangkapan lebih kecil yang disebut sub-DAS. Akibatnya, ada
kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan seluruh tangkapan untuk
memastikan bahwa kegiatan yang merusak seperti polusi tidak berdampak
pada orang lain di kawasan tangkapan air atau di perairan pantai.
Baru-baru
ini pengelolaan lahan dan air telah semakin didasarkan pada daerah
tangkapan dan 'pendekatan tangkapan atau DAS', serta yang terutama
adalah interaksi dari keduanya. Pendekatan ini telah digunakan untuk
membawa perbaikan lingkungan, khususnya pada skala yang luas di mana
perubahan yang diperlukan di daerah yang melibatkan banyak pemilik
lahan, dan penggunaan beberapa lahan air. Penelitian dapat diatur dan
terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek berbasis DAS yang
bertujuan untuk perbaikan lingkungan. Sungai yang mengalir DAS (daerah
aliran sungai) adalah integrator alami yang merespon kegiatan di kawasan
tangkapan air dimana debit sungai bermuara (laut, danau, lahan basah).
Pendekatan ini secara eksplisit mensyaratkan pengembangan kemitraan
antara orang-orang pengambil keputusan pengelolaan lahan dan air,
sehingga tujuan mengintegrasikan segala keputusan adalah untuk
memastikan bahwa tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan budaya untuk mereka
yang terkena dampak (tinggal disekitar DAS) terpenuhi sebanyak mungkin.
Kemitraan juga mempertemukan si penyebab masalah dengan mereka terkena
dampak oleh mereka. Diharapkan dengan identifikasi masalah dan
pengambilan keputusan secara bersama akan membawa perbaikan jangka
panjang atas tanah dan pengelolaan air.
Pengelolaan
daerah tangkapan air yang lebih baik di bawah manajemen perencanaan
tangkapan secara resmi (baik sukarela atau peraturan), Peraturan
ditingkatkan dan aksi masyarakat dapat berefek pengurangan yang besar
dalam pengiriman polutan ke perairan pesisir.
Beberapa Prioritas Pengelolaan yang dapat diatasi diatasi Melalui Proses ICZM :
• Mengidentifikasi Polutan Prioritas di daerah Tangkapan, terutama polutan yang mencemari ekosistem pesisir dan terumbu karang;
• Mengidentifikasi Praktek Pengelolaan Lahan yang Efektif yang efektif untuk mengurangi polusi;
• Mengelola Hutan,
pertanian dan pembangunan perkotaan untuk pengurangan sedimen, nutrisi
dan pestisida. Kontrol erosi, manajemen pupuk, pengelolaan limbah hewan
dan manajemen penggunaan pestisida juga akan menjadi bagian penting;
• Mengembangkan Kode Etik untuk penebangan untuk mengurangi erosi, dan meminimalkan erosi dari area penyimpanan dan penanganan kayu. Namun Peraturan tentang Loggin harus jelas dan ditegakkan.
• Mempertahankan Tanaman untuk Melindungi Tanah,
seperti tebu, kelapa sawit dan pisang. Mempertahankan residu ini dapat
mengurangi erosi secara nyata, terutama pada tahap penanaman setelah
persiapan lahan. meminimalisir atau mengurangi sistem pembalakan dalam
sistem cara tanam juga mengurangi erosi secara signifikan. Pencegahan
pembukaan lahan dan tanam di lereng sangat curam sangat penting dalam
pengendalian erosi, walaupun seringkali sulit untuk dilakukan karena
peraturan kepemilikan tanah;
• Mengelola Penggunaan Pupuk.
Kebanyakan sistem tanam menggunakan pupuk 'berlebih' dari persyaratan
serapan hara merupakan proses yang tidak efisien (hanya 40% pupuk
nitrogen atau fosfor yang diterapkan terserap oleh tanaman). Beberapa
petani percaya bahwa jika pemberian pupuk lebih banyak akan lebih baik.
Kelebihan aplikasi pupuk menyebabkan kerugian besar N dan P ke saluran
air. Peningkatan pengelolaan melalui memberikan nasihat kepada petani
dan kontrol ketat terhadap 'kelebihan' penggunaan pupuk dapat
mengakibatkan penurunan signifikan nutrisi di perairan;
• Perangkap Sedimen dan Nutrisi
dari peternakan di daerah pinggiran sungai, saluran air dan vegetasi
lahan basah (alami dan buatan) akan mengurangi debit sedimen dan nutrisi
ke perairan pesisir. Satu peringatan, sistem perangkap ini kurang
efektif pada daerah dengan curah hujan tinggi dimana volume air besar
dan waktu tinggal air di daerah 'buffer' pendek. Biasanya terlalu pendek
untuk memungkinkan terjadinya denitrifikasi, N dan serapan P oleh
tanaman, sedimentasi, kerusakan herbisida atau adsorpsi ke dalam tanah /
sedimen dalam jangka panjang;
• Menjaga Hamparan Tanaman Penutup
seperti padang rumput sangat penting dalam mencegah erosi. Penghapusan
tanaman penutup oleh penebangan pohon menyebabkan peningkatan erosi
secara besar-besaran pada lereng bukit dan erosi tebing sungai.
Mengelola penggembalaan diinduksi erosi dengan mempertahankan penutup
rumput adalah mungkin, tetapi rumit oleh curah hujan yang tidak teratur
sering dialami di daerah tropis kering dimana kekeringan dapat diikuti
oleh curah hujan besar selama siklon (badai) dan musim hujan;
• Mengontrol Perkembangan Perumahan dan Pariwisata
sangat penting. Namun biasanya dilakukan dengan pengelolaan lahan yang
sangat rendah/buruk. Biasanya lahan benar-benar dibersihkan dari semua
vegetasi (baik rumput, pohon atau bahkan gulma), sering kali pembersihan
terjadi pada musim hujan di lereng bukit curam sangat curam yang
'dipotong dan diisi' untuk rumah dan hotel situs dan jalan. Upaya untuk
mengelola perkembangan tersebut secara mengejutkan sulit untuk
diterapkan karena kekuatan 'pengembang' terutama di dekat daerah pantai
yang menarik. Pedoman yang kuat sering ada untuk pembangunan perkotaan '
gangguan tanah yang minimal', tetapi hanya beberapa kasus di mana
pedoman ini berhasil dilaksanakan. Untungnya potensi penurunan erosi
setelah perkembangan perkotaan menjadi mapan dan vegetasi
direhabilitasi;
• Pengelolaan Limbah Pertambangan dan Industri;• Mengelola Air Limbah Rumah Tangga dan Industri. Manajemen limbah perkotaan akan menjadi prioritas di banyak tempat, • Mengontrol Pembuangan Air ke dalam Sungai dan Pantai. Aturan operasional untuk bendungan dan jaringan irigasi akan menjadi komponen penting;
• Menetapkan Target Pengurangan Debit Polutan ke Perairan Pesisir.
Dalam semua proyek mitigasi polusi gagasan tentang target adalah
penting misalnya berapa tingkat pengurangan yang diperlukan dan dalam
jangka waktu berapa lama untuk melindungi ekosistem (misalnya terumbu
karang). Target sebaiknya dipertimbangkan dalam konteks target SMART (Specific, Measurable , Achievable, Relevan, Timed) yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan memiliki jangka waktu batas).
• Pemantauan dan Penilaian pada Skala 'Tangkapan ke Karang'. Menilai
efektivitas pengelolaan tanah dengan pemantauan di lingkungan laut
(yaitu di karang) merupakan sesuatu yang kompleks, mahal dan butuh waktu
yang lama. Akan lebih baik untuk memantau pada skala intervensi yaitu
manajemen pada akhir paddock, pada ujung pipa saluran pembuangan, di
sebuah sungai kecil atau pada hilir sungai di mana limbah itu dibuang ke
laut;
REKOMENDASI PENGELOLAAN DAERAH TANGKAPAN DAN TERUMBU KARANGRekomendasi 1: Pemetaan dan YurisdiksiSebelum pengelolaan daerah tangkapan hulu dapat mulai, adalah penting untuk menentukan:• Ukuran, dan apa saja yang ada di daerah tangkapan air; • Apa Instansi yang bertanggung jawab, peraturan yang ada dan program pengelolaan yang sedang berjalan; • Siapa saja orang-orang dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS, terutama mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan yang merusak, dan • Apakah ada hak kepemilikan tradisional di daerah tersebut. Rekomendasi 2: Mengidentifikasi dan Memprioritaskan Isu-isu untuk Memilih Respon Manajemen.
Analisis Masalah Utama adalah Anda harus tahu apa masalah utama dari tangkapan yang merusak terumbu karang sebelum memulai tindakan apapun.
Oleh karena itu, adalah penting untuk menentukan apa masalahnya,
menilai biaya kerugian akibat kerusakan dan juga biaya yang dibutuhkan
dalam mencari solusi, dan menentukan berbagai solusi. Hal ini penting
untuk dapat menempatkan apa yang Anda coba capai dalam beberapa kalimat
(VISI). Misalnya, ada kebutuhan untuk menganalisis masalah kualitas air
di daerah tangkapan air yang mempengaruhi ekosistem laut. Visi yang baik
akan membantu memprioritaskan masalah yang harus diatasi pertama kali,
menganalisis pengelolaan yang memungkinkan, Prioritas pengelolaan dan
peraturan, serta menentukan biaya yang dibutuhkan. Analisis ini juga
harus mencakup penentuan sumber pendanaan dan keahlian, seperti dari
pemerintah pusat,daerah, lokal, PBB dan negara-negara donor, LSM lokal
dan internasional, atau narasumber lokal. Output dari anlisis ini akan
menginformasikan program pengelolaan daerah tangkapan air didasarkan
pada analisis dan harus dimiliki/dipahami secara lokal.
Rekomendasi 3. Meningkatkan Kesadaran dan Solusi dari Masalah.
Seringkali
orang tidak menyadari bahwa tindakan mereka menyebabkan kerusakan pada
daerah hilir. Dengan informasi yang baik dan bahan yang jelas, sangat
mungkin untuk membentuk kemitraan dengan orang-orang yang tinggal dan
bekerja di hulu daerah tangkapan air untuk memecahkan masalah yang
terjadi di hilir.
Rekomendasi 4: Kontrol Input Sedimen
Untuk
mengontrol dan mencegah kelebihan aliran sedimen ke daerah pesisir
Anda, penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber, menilai dan memantau
arus sedimen, dan melaksanakan tindakan untuk mengurangi aliran sedimen
tangkapan. Langkah-langkah spesifik adalah sebagai berikut:
Rekomendasi 5: Kontrol Input Nutrien (Nitrogen dan Fosfor)
Jika peningkatan beban nutrisi menyebabkan masalah (mirip dengan Rekomendasi
# 4 di atas), tugas-tugas penting adalah: analisis masalah utama untuk
menentukan sumber utama, tindakan yang mungkin untuk mengukur
konsentrasi nutrisi utama (nitrogen dan fosfor), meningkatkan kesadaran
di masyarakat tangkapan dari masalah dan solusi yang mungkin, dan
melaksanakan tindakan korektif yang mudah untuk mengurangi sumber utama.
Kemungkinan kenaikan sumber utama karena:
i) Limbah
buangan dari pabrik pengolahan limbah yang tidak memadai, tidak efektif
atau sistem septik yang buruk dipertahankan yang berasal dari kota-kota
dan rumah;ii) Kerugian pupuk dari pertanian intensif, terutama dari tebu, kelapa sawit, hortikultura (buah dan sayuran), umbi-umbian, tanaman biji-bijian. iii) Sistem produksi ternak intensif, seperti peternakan babi, ternak yang butuh banyak pakan, produksi ayam, budidaya (udang / udang, ikan); iv) Air hujan dari perkotaan mengandung seperti pupuk, deterjen dan limbah lainnya seperti kotoran hewan, dan v) Industri sekunder, seperti pabrik pengolahan makanan dan pengalengan, tempat pemotongan hewan, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan. Rekomendasi 6: Kontrol Input Pestisida dan Kimia Beracun lainnya
Polutan
yang paling sulit untuk mendeteksi dan mengukur adalah pestisida dan
polutan organik persisten lainnya (POPs), tetapi ini bisa dilakukan
karena polutan ini menyebabkan kerusakan besar pada hewan dan tumbuhan
dalam ekosistem pesisir. Jika Anda menduga bahwa peningkatan beban
pestisida adalah masalah bagi daerah Anda, penting untuk
mengidentifikasi mengukur senyawa dan konsentrasi mereka dengan analisis
ilmiah secaa rinci dan seringkali mahal. Dengan data ilmiah dan
analisis masalah secara umum penting untuk: menentukan apa yang menjadi
sumber dan senyawa utama, meningkatkan kesadaran di bidang sumber tanpa
menyalahkan, dan mengembangkan program-program untuk mengurangi jumlah
yang digunakan serta beralih ke senyawa kurang beracun. Meningkatnya
beban polutan mungkin karena:
i) Pertanian, khususnya tanam tebu, kelapa sawit, sayuran, buah, dan tanaman biji-bijian termasuk beras dan jagung;ii) Perkotaan, termasuk menggunakan pengendalian malaria dan gulma; iii) Bahan Kimia Sintetis misalnya pengawet kayu, obat-obatan dari limbah pembuangan limbah, termasuk sintetis hormon; iv) Pelepasan tidak sengaja atau ilegal dari industri Rekomendasi 7: Limbah Padat dan Plastik
Limbah
padat dan plastik mudah untuk dilihat dan menjadi masalah bagi daerah
pesisir, tugas penting kita adalah menentukan besar sumber, kurangnya
fasilitas pengumpulan limbah padat, kurangnya kesadaran masyarakat, atau
rendahnya pengawasan pemerintah terhadap industri. Polutan utama adalah
plastik dan kaca (terutama botol), logam, kain, kertas dan kardus.
Rekomendasi 8: Limbah Logam Berat dan Pertambangan serta Industri Lainnya
Masalah
utama dengan logam berat adalah bahwa mereka tetap dalam ekosistem
untuk waktu yang sangat lama dan akan terakumulasi dalam hewan dan
tumbuhan. Dengan demikian, beberapa logam berat dapat memasuki rantai
makanan manusia, seperti merkuri, kadmium dan timbal dalam seafoods.
Jika ada bukti dari logam beracun di sungai dan laut di daerah Anda,
Penekanan harus pada sumber-sumber besar, seperti: i) Pertambangan dan Pengolahan Mineral; ii) Industri Manufaktur (produksi terutama baterai dan elektro-plating); iii) Operasi Pelabuhan dengan Penggunaan cat antifouling, Tumpahan dari Pengiriman Bijih dan Logam limpasan air dari pelabuhan, dan iv)
Pertanian yang akan menjadi sumber pencemaran difus (residu kadmium
dalam pupuk, merkuri dalam fungisida, senyawa tembaga sebagai fungisida,
senyawa selenium dalam racun tikus).Rekomendasi 9: Mengurangi Kerusakan dari Banjir Akibat Modifikasi Daerah Tangkapan.
Hindari
memodifikasi daerah resapan untuk mengurangi aliran volume besar air
yang membawa sedimen, nutrisi dan bahan padat setelah hujan lebat.
Daerah resapan alami yang sehat bertindak seperti spons dengan
memperlambat pelepasan air tawar dan memungkinkan banyak untuk menyerap
ke dalam tanah. Daerah resapan sehat dapat mengurangi erosi dan banjir
serta polusi karena pengiriman air dari hujan deras telah diperlambat.
Jika memungkinkan perbaiki DAS yang rusak dengan mencegah pembukaan
hutan, pengelolaan hutan yang buruk, merehab daerah yang rusak,
mempertahankan dan memperbaiki zona riparian di samping sungai,
mengurangi luas permukaan beton/berlapis dengan menggantinya dengan
sabuk intermiten vegetasi seperti rumput, pasir atau kerikil;
mempertahankan kolam alami dan lahan basah di daerah drainase, dan
menghapus sampah dan bahan padat lainnya yang dapat dibawa pergi dengan
air banjir.
Rekomendasi 10: Adaptasi Tangkapan dan Pesisir Terhadap Perubahan Iklim.
Sebagian
besar dari efek merusak dari tangkapan terumbu karang yang dibahas akan
meningkat seiring dengan iklim global yang terus berubah. Oleh karena
itu, Rekomendasi 1 sampai 9 di atas juga harus ditekankan sebagai
langkah adaptasi perubahan iklim. Anda harus menemukan cara yang efektif
untuk adaptasi perubahan iklim dan memperkuat semua langkah-langkah
lain untuk mencegah kerusakan dari tangkapan dengan menekankan bahwa
perubahan iklim akan memperburuk keadaan. Namun, tidak harus diambil
perawatan untuk fokus pada dampak perubahan iklim di masa depan dengan
mengorbankan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan daerah
tangkapan air masa sekarang, walaupun pengelolaan tangkapan untuk
persiapan perubahan iklim dapat membuka peluang untuk pendanaan.
Rekomendasi #1 sampai #9 akan membantu dalam beradaptasi
daerah tangkapan dan pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Manajemen
yang baik dari daerah tangkapan akan mengurangi kerusakan di masa depan
dari perubahan iklim, terutama dari cuaca lebih sulit diprediksi, badai
besar, kenaikan permukaan air laut dan peningkatan suhu di atmosfer dan
laut.
Rekomendasi 11: Carilah Bantuan dari Donor dan Konvensi
Sebagai
Pengelola sebuah daerah pesisir, kita harus mencari tahu proyek-proyek
di Negara kita yang berhubungan dengan pengembangan tangkapan dan
belajar dari mereka bagaimana pengelolaan itu diatur dan didanai. Ada
sejumlah lembaga donor dan dari pemerintah yang memiliki program
pengelolaan daerah tangkapan yang mungkin dapat membantu, namun
lembaga-lembaga internasional dan PBB mengharuskan permintaan datang
dari pemerintah negara. Periksa konvensi regional dan internasional yang
berlaku untuk pengelolaan pesisir dan DAS untuk menentukan apakah dapat
diterapkan pada masalah yang timbul dari daerah tangkapan dan juga
apakah dapat memberikan rekomendasi dana untuk perbaikan. Banyak juga
LSM internasional maupun regional yang dapat membantu dengan
proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan wilayah pesisir
dari daerah resapan.
SUMBER:http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3A11-rekomendasi-pengelolaan-daerah-tangkapan-dan-konservasi-terumbu-karang&catid=54%3Apengelolaan&Itemid=52&lang=en
|
Adalah salah satu LSM di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 Februari 2005. LSM ini dibentuk dan dikelola secara independen oleh beberapa orang aktivis masyarakat perikanan yang punya kepedulian terhadap pelestarian Sumber Daya Laut dan Pesisir di daerah ini.
Jumat, 16 Agustus 2013
Rekomendasi Pengelolaan Daerah Tangkapan dan Konservasi Terumbu Karang
Konservasi Terumbu Karang, Asa Alternatif Ekonomi Masyarakat Lokal
Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan
secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya melindungi
melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang
akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau
kecil, pemerintah telah menetapkan kebijakan
penetapan target nasional konservasi
laut yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada pertemuan Convention on Biological
Diversity (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencanangan target
10 juta hektar kawasan konservasi Laut pada tahun 2010, dan
selanjutnya target 20 juta hektar pada tahun 2020, sebagaimana
pernyataan Presiden mengenai Coral Triangle Initiative (CTI) dalam
forum APEC Leaders Meeting di Sydney,
2007.
Mandat CBD mengamanatkan setiap negara melaksanakan pengelolaan efektif
kawasan konservasi perairan sebesar 10 (sepuluh) persen dari wilayah teritorial
lautnya. Indonesia memiliki wilayah teritorial laut seluas lebih kurang 310
juta hektar, komitmen Indonesia untuk
mengelola 20 Juta Hektar Kawasan Konservasi pada tahun 2020 masih baru
menjangkau sekitar 6 (enam) persen, belum memenuhi total 10 (sepuluh) persen
wilayah teritorial yang terhitung mencapai tidak kurang dari 31 juta hektar.
Komitmen konservasi tentu merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan
nelayan lokal, mengingat wilayah terumbu karang berada di kawasan perairan
pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk perikanan
berkelanjutan bagi masyarakat, bukan untuk nelayan besar atau eksploitasi
sumberdaya yang berlebihan. Dukungan kebijakan kebijakan nasional dalam
pengembangan kawasan konservasi perairan dibuat secara menyeluruh dan terpadu
serta mempertimbangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Berbagai
kebijakan, peraturan, pedoman terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan
telah dikembangkan.
Paradigma
baru pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, semakin
memperkuat keberpihakan konservasi terumbu karang untuk kesejahteraan
masyarakat lokal, paradigma ini paling tidak memuat dua hal penting, pertama: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem
ZONASI. Paling tidak, ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di
dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona
perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona perikanan berkelanjutan tidak pernah
dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi kawasan
konservasi terdahulu baik menurut UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998. Kedua: Desentralisasi
Kewenangan Pengelolaan,
yakni pengelolaan kawasan
konservasi yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat saja, kini berdasarkan
UU
No. 27 Tahun 2007 (Lebih lanjut, pengaturan mengenai kawasan konservasi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor: Per.17/Men/2008) dan PP No. 60 Tahun 2007 serta Permen Men KP no
Per.02/Men/2009, Pemerintah
daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya.
Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008, khususnya
terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut
dan konservasi.
Pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan
kawasan konservasi serta
perkembangan desentralisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, jelas hal ini
merupakan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Kekhawatiran akan mengurangi
akses nelayan yang disinyalir banyak pihak dirasakan sangat tidak mungkin. Justru hak-hak tradisional
masyarakat sangat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat
diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona
perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan,
maupun zona lainnya), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan
maupun pariwisata bahari dan lain sebagainya. Pola-pola seperti ini dalam
konteks pemahaman konservasi terdahulu (sentralistis) hal ini belum banyak
dilakukan. Peran Pemerintah pusat dalam
konteks ini, hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi, sedangkan
proses inisiasi, identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara
keseluruhan dilakukan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hak-hak
tradisional masyarakat adat sangat dijaga dalam pengelolaan konservasi kawasan
yang dilakukan, pun demikian manfaat kawasan konservasi yang diperoleh
sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat lokal, seperti Contoh pengelolaan kawasan konservasi di Bintan, melalui program coremap
telah dikembangkan mata pencaharian alternatif pengelolaan kepiting bakau di
KKP-D. Hasilnya cukup lumayan, bahkan dapat dijadikan wisata saat pemanenannya
(wisata kuliner/seafood kepiting). di Raja Ampat, dikelola dengan sistem
Pungutan Konservasi berupa PIN bagi pengunjung KKP-D untuk kegiatan menyelam
dll. Sistem buka tutup (sasi) yang dikembangkan di Kawasan Kawe - Raja Ampat
telah memberikan hasil ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. KKP tersebut
ditutup 1 tahun dan dibuka di akhir periode, dengan hasil lebih Rp.1,5 juta hanya
dalam waktu 1 minggu saja.
Terdapat
sejumlah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di lokasi binaan COREMAP
II, sebagaimana ditulis dalam “Konservasi sumberdaya Ikan
berbasis Kearifan Lokal”. Diantaranya di wilayah barat, salah satu
kegiatan ekonomi yang diminati dan memiliki prospek yang baik adalah budidaya
perikanan. Jenis-jenis kegiatan budidaya perikanan tersebut antara lain; (i)
pembesaran ikan kerapu, (ii) pembesaran kepiting bakau, dan (iii) pembesaran
ikan lele. Kegiatan ini meskipun mempunyai siklus panen yang relatif panjang
(rata-rata 3 s/d 8 bulan), tetapi dengan pengelolaan waktu yang efektif
kegiatan budidaya ini tetap memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat
yang melaksanakannya. Hingga tahun 2010 kegiatan pembesaran
ikan kerapu, kepiting bakau dan ikan lele yang masih berjalan dan sedang dalam
pengembangan adalah di Batam (pembesaran ikan kerapu), Lingga (pembesaran ikan
kerapu), Bintan (kepiting bakau) dan ikan lele (Tapteng). Meskipun
kegiatan pembesaran ikan kerapu di Batam belum memberikan peningkatan
pendapatan secara langsung bagi kelompok-kelompok masyarakat, akan tetapi
sejumlah kelompok masyarakat telah melakukan panen beberapa kali, yaitu di
Pulau Mubud, Pulau Abang dan Pulau Karas. Secara umum, 1 kelompok masyarakat (1
KK) mendapat dukungan pembiayaan sebanyak Rp. 15 juta, dalam masa 8 bulan akan
panen dengan hasil Rp. 15 juta. Hasil ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Rp. 4
juta digunakan untuk membeli bibit baru, Rp. 3 juta digunakan untuk mencicil
pinjaman, dan Rp. 8 juta digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga selama 8
bulan, jadi rata-rata Rp. 1 juta perbulan. Saat proses pembesaran, anggota
kelompok masyarakat ini telah menjalankan aktifitas penangkapan ikan dengan
jadual yang tetap (seperti biasanya) karena pembesaran ikan kerapu tidak
membutuhkan waktu yang banyak dalam pemeliharaannya. Hasil tangkapan yang
kualitasnya bagus akan dijual dan selebihnya digunakan sebagai pakan.
Pendapatan kelompok masyarakat menangkap ikan sekitar Rp 500 – Rp. 750 ribu
perbulan. Untuk kegiatan pembesaran ikan lele di
Tapteng mengalami perkembangan yang cukup pesat. Umumnya kelompok masyarakat
mulai mengembangkan kegiatannya dengan menambah kolam yang tadinya hanya 1 unit
sekarang menjadi 3 sampai 4 unit kolam dengan biaya sendiri. Investasi awal
yang digunakan oleh setiap kelompok (1 KK) sekitar Rp. 3 juta. Dalam waktu 3 bulan,
ikan peliharaan dipanen, dan dari panen diperoleh hasil rata-rata sebesar Rp.
400 – Rp. 600 ribu setiap unit kolam, sehingga dengan 3 unit kolam mereka
memperoleh hasil rata-rata Rp. 1.200.000 – Rp. 1.600.000. Sebelum melakukan
kegiatan pembesaran ikan lele anggota kelompok masyarakat memiliki aktifitas
memancing dan berdagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 600 ribu.
Dengan adanya kegiatan pembesaran ikan lele ini, pendapatan kelompok masyarakat
menjadi meningkat. Sementara kegiatan
pembesaran kepiting bakau meskipun telah beberapa kali panen, tetapi hasilnya
masih digunakan untuk pengadaan bibit dan pakan. Hal ini disebabkan karena
kelompok masyarakat belum mampu meningkatkan kapasitas produksi. Beberapa
faktor yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai dengan perencanaan karena
pencurian kepiting oleh monyet dan banyaknya kepiting yang lepas. Akan tetapi,
kegiatan pembesaran kepiting bakau ini memiliki nilai lebih karena lokasi dan
penataan tempatnya cukup baik, sehingga areal pembesaran dijadikan sebagai
lokasi wisata dan edukasi bagi siswa sekolah.
Berkembangnya kegiatan
budidaya ikan kerapu di Batam dan budidaya ikan lele di Tapteng telah mampu
mengispirasi masyarakat yang lainnya (di luar kelompok binaan COREMAP II) untuk
mencoba bahkan menggeluti dengan lebih serius kegiatan budidaya ini secara
swadaya (kemampuan sendiri). Kegagalan usaha yang selama ini menghantui masyarakat seakan sirna dan
berganti dengan semangat serta keyakinan yang tinggi bahwa kegiatan budidaya ini
akan memberikan keuntungan/manfaat yang besar bukan hanya secara ekonomi
(pendapatan meningkat), tetapi juga akan memberikan jaminan kelestarian
sumberdaya terumbu karang dan asosiasinya. Kelompok masyarakat di
Pulau Mubud, Pulau Karas dan Pulau Abang secara kontinyu mengawasi serta
menjaga lingkungan perairan agar terhindar dari pencemaran akibat tumpahan
limbah kapal, rusak akibat praktek perikanan destruktif, sampah rumah tangga
dan lain-lain, karena semuanya itu akan mengganggu kegiatan budidaya yang
mereka lakukan.
Tak berbeda
dengan di wilayah barat, di wilayah
timur terlaksana kegiatan budidaya yang cukup potensial seperti budidaya rumput
laut di Kabupaten Biak Numfor, Buton, Sikka dan Wakatobi. Contohnya yang telah dikembangkan oleh masyarakat di kawasan
pulau Pai dan Nusi ,Kabupaten Biak sebagai mata pencaharian alternatif yang sangat digemari oleh
masyarakat setempat. Hal ini selain
pemeliharaannya mudah, cepat panen juga ada yang menampung hasilnya. Selama ini
masyarakat melakukan budidaya rumput laut hanya masih sebatas “pilot project” yang awalnya dibantu oleh
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak.
Walaupun demikian
masyarakat mulai bisa merasakan bahwa budidaya rumput laut ini cukup
menjanjikan karena pasarnya sudah jelas.
Pada saat ini pengembangan rumput laut masih terbatas dari segi luasan
maupun minat dan pengetahuan masyarakat akan budidaya rumput laut. Oleh karena itu kedepan perlu penelitian yang
lebih seksama pada daerah lain untuk pengembangannya yang secara lingkungan
cukup potensial. Kendala utama yang
dihadapi masyarakat sekarang ini adalah masalah pengetahuan, sumber bibit dan
modal awal. Melalui program pengembangan
mata
pencaharian alternatif dalam pemngelolaan kawasan konservasi terumbu karang di wilayah COREMAP II, maka usaha ini bisa menjadi
solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan mata pencaharian
alternatif yang
dapat diandalkan di Kabupaten Raja Ampat adalah usaha ikan hidup di Kampung
Manyaifun. Kegiatan ini dilakukan oleh Bapak Elias Maturuti. Kegiatan ini
dilihat oleh pihak program cukup strategis untuk mengintervensi peminimalan
cara tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Melalui Pak Elias diminta untuk tidak membeli ikan dari nelayan yang
melakukan penangkapan dengan cara yang tidak ramah dan ikut membantu
menyampaikan pesan konservasi kepada para nelayan yang memasok ikan hidup.
Adapun dana perolehan awal yaitu sebesar
Rp. 10.000.000,- di peruntukan penambahan modal pembelian ikan hidup
terhadap masyarakat serta renovasi keramba penampung. Hal ini dirasakan sangat
bermanfaat karena selama ini hanya mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya
pas-pasan sekarang telah terbantu dengan fasilitas yang mudah diakses serta
mengerti kondisi obyektif di lapangan. Disamping itu adanya pembekalan secara
informal yang dilakukan staf lapangan terhadap manajemen usaha yang baik sangat
mempengaruhi jalanya usaha yang ditekuninya.
Kegiatan budidaya ikan hias dan ikan hidup di Indonesia wilayah bagian Timur meskipun
belum dimanfaatkan secara optimal, namun budidaya ini merupakan salah satu mata pencaharian
alternatif di bagian zona perikanan berkelanjutan pada kawasan konservasi
perairan yang
potensial serta dapat membuat masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga
lingkungan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Selain di Kawasan
Konservasi, kegiatan budidaya perikanan juga dilakukan di area pemanfaatan umum
wilayah pesisir dan laut desa mereka. Oleh karena itu program COREMAP II II memfasilitasi
masyarakat mengembangkan potensi ikan hias ini, salah satunya adalah di
kabupaten Pangkep yang telah mampu menjalin jalur pemasaran dengan pihak
eksportir di Jakarta. Sampai dengan tahun 2009, telah ada 3 kelompok nelayan di
Pangkep dan 1 kelompok di Buton yang mengikuti program dan telah memiliki
jaringan perdagangan dengan eksportir yang berstatus memiliki sertifikasi
Marine Aquatic Council (MAC). Proses Sertifikasi untuk kedua lokasi
dilaksanakan pada tahun 2010 lalu.
Kegiatan budidaya kepiting
juga teah diupayakan di kawasan konservasi serta disekitar daerah perlindungan
laut masyarakat pada lokasi
program COREMAP II wilayah timur khususnya di Kab Biak dan Buton. Di Kabupaten
Biak budidaya kepiting ini telah dicoba dan diusahakan oleh mayarakat kampung
Mnurwar Distrik Oridek. Kegiata ini
cukup berhasil, namun kondisi prasarana pendukung seperti bahan keramba
yang masih sederhana hanya menggunakan patok-patok bambu sehingga banyak
kepiting yang akhirnya lolos. Selain itu
tingkat pengetahuan mereka tentang tehnik budidaya ini juga masih sangat
terbatas. Dari sisi pasar pada saat itu
sudah terdapat permintaan secara kontinyu. Pengembangan budidaya ini belum
optimal tetapi potensi usaha ini cukup besar. Ke depan budidaya ini perlu
mendapat perhatian sebagai salah satu mata pencaharian alternatif yang cukup prospektif. Hal ini juga
terjadi di Kabupaten Buton ,sehingga penguatan dan pengembangan dari berbagai
pihak sangat dibutuhkan.
Dalam mendukung
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, harapan ekonomi tak hanya
berkembang di wilayah perairan dan sekitar kawasan konservasi saja. Usaha
masyarakat di bidang perdagangan
juga berkembang di beberapa wilayah COREMAP, salah satu contohnya di Raja
Ampat. Perolehan dana alternative
Income Generation ‘distrik Fund’
sejumlah Rp. 15.000.000,- telah merubah total kehidupan Bapak Ma Udin Kampung
Yenwaupnor. Dengan
bermodalkan semangat ingin membantu masyarakat kampung serta pengalaman kerja
dagang kaki limanya di tambah dengan kepercayaan yang di berikan oleh petugas
Lapangan Coremap II Kabupaten Raja Ampat, Bpk. Ma Udin dengan kiosnya telah
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Yenwaupnor pada umunya dan dengan
kiosnya pula Bpk. Ma Udin sekarang telah memperoleh Omzet Perbulan berkisar 15
Juta sampai dengan 25 juta perbulan dengan keuntungan bersih bisa mencapai 5
juta sebulan. Keberhasilan ini di peroleh dari pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat yang berbanding lurus dengan kepentingan Bisnis. Selain kegiatan
usaha kios Pak Ma Udin juga pembeli ikan asin dari masyarakat dengan
memperhatikan harga yang saling menguntungkan dengan pihak penjual. Komitmen
ini yang dipegang Pak Ma Udin untuk ikut mengembangkan ekonomi masyarakat
setempat. Di
desa Gerak Makmur kabupaten Buton juga telah berkembang kedai/warung yang
menjual beberapa bahan pokok, mereka menyebutnya dengan ‘Kedai COREMAP’, kedai
ini mampu menyuplai kebutuhan pokok masyarakat bahkan bahan bakar yang
diperlukan oleh nelayan desa sekitarnya seperti desa Lapandewa Makmur,
Burangasi, Lakaliba dan Lapandewa.
Tingkat
partisipasi masyarakat yang tinggi untuk turut mengelola kawasan konservasi
perairan yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah di beberapa daerah
sebagaimana dikemukakan tersebut, jelas
menganulir pernyataan pihak tertentu bahwa program konservasi terumbu karang yang dilakukan
melalui program COREMAP membatasi
akses nelayan tradisional dan mengabaikan kearifan lokal dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya laut. Pernyataan pihak dimaksud jelas tidak beralasan, contohnya
di Wakatobi, dalam
pelaksanaan COREMAP II, kolobarasi
antara pemerintah daerah, masyarakat dan pengelola
taman nasional Wakatobi berjalan dengan baik, masyarakat mempunyai ruang
membuat DPL (Daerah Perlindungan Laut) di zona pemanfaatan tradisional Taman
Nasional. Ada 28 DPL yang diinisiasi masyarakat di Wakatobi, kemudian secara keseluruhan
lokasi program COREMAP II lebih dari 400 DPL telah diinisiasi dan dikelola oleh
masyarakat lokal. Jadi tidak benar jika Masyarakat nelayan tidak dilibatkan
dalam pembentukan pengelolaan konservasi wilayah pesisir. Proses pembentukan DPL-DPL
di seluruh desa COREMAP II sejak awal diinisiasi masyarakat terlibat dan aktif
berpartisipasi, proses identifikasi potensi desa, konsultasi publik, sampai
pengesahan/penetapan oleh Desa seluruhnya berbasis masyarakat. Masyarakat
secara partisipatif membuat peta/denah lokasi DPL, menyusun aturan pengelolaan
yang kemudian dikukuhkan aturannya dalam Peraturan Desa (PERDES). Rencana
pengelolaan terumbu karang (RPTK) yang merupakan petunjuk dan arahan bagi desa
dalam mengelola DPL, disusun dan dibuat oleh masyarakat dengan dibantu oleh
beberapa fasilitator. DPL-DPL tersebut
merupakan bagian “No Take Area” dari
Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten. Disamping itu, program COREMAP II telah
memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Suku Bajo khususnya di wilayah
Sulawesi Tenggara. Sebagai bagian proses pembelajaran, buku “Bajo Berumah di Laut
Nusantara”, telah diterbitkan oleh COREMAP II.
Beberapa
penuturan cerita
di atas, merupakan pembelajaran COREMAP II, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan
mata
pencaharian alternatif sangat
penting dalam sebuah program yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam
memelihara alamnya serta mengelola kawasan konservasi terumbu karang yang
lestari. Para pelaku pencaharian alternatif ini dapat menjadi mitra pelaku
konservasi, karena masyarakat akan
memelihara alam jika mereka mendapat manfaat ekonomi dari alam itu. Sementara “Kedai COREMAP”
tidak kalah membanggakan, karena kedai ini telah mampu menyuplai kebutuhan
pokok masyarakat, bahkan bahan bakar untuk kebutuhan nelayan melaut.
Berdasarkan paparan keberhasilan program mata pencaharian alternatif, maka
pelibatan masyarakat sebagai mitra pelaku konservasi adalah upaya COREMAP untuk
mengubah perilaku masyarakat dalam memelihara kelestarian ekosistem terumbu
karang dan asosiasinya. Teramat jelas guratan asa alternatif ekonomi masyarakat
lokal tergambar dari semangat dan upayanya melestarikan terumbu karang. Semoga
upaya positif ini tetap terjaga untuk mewujudkan terumbu karang sehat, ikan
berlimpah dan masyarakat yang sejahtera. (sji)
SURAJI
surajis.wordpress.com
http://suraji78.blogspot.com
http://suraji.s5.com
Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan
Head of Conservation Area Protection and Preservation
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Ditjen KP3K - Kementerian Kelautan dan Perikanan
Directorate of Conservation Area and Fish Species, Directorate General of Marine, Coasts and Small Islands, Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gd. Mina Bahari III lt. 10 Jakarta Pusat. T./F. +62 21-3522045
GAMBARAN SOSIAL EKOMONI MASYARAKAT PESISIR DESA COREMAP II KABUPATEN BUTON
Oleh: Ma'ruf Kasim, PhD
PENDAHULUAN
Keberhasilan Coremap salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan, potensi dan aspirasi masyarakat. Untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat diperlukan data base sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang. Di samping dapat digunakan sebagai masukan dalam mendisain program, data base aspek sosial-ekonomi terumbu karang juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Data base sosial-ekonomi ini merupakan titik awal yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program/intervensi Coremap dilakukan.
Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan Coremap Fase II. Dalam implementasi program Coremap II Kabupaten Buton yang telah dilaksanakan meliputi; penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan lain. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan di bidang sarana prasarana, pihak Coremap II telah memberikan bantuan berupa dana Block Grant pada masing-masing desa di wilayah program. Begitu pula halnya dengan pengembangan di bidang ekonomi, pihak Coremap II telah meluncurkan dana AIG dan Seed Fund. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya dengan tidak merusak lingkungan pesisir.
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Hasil analisis survei pada 11 Kecamatan Wilayah coremmap II dan tersebar pada 20 Desa/Kelurahan memperlihatkan bahwa, masyarakat yang bergerak sektor nelayan tradisional mempunyai tingkat pendidikan relatih rendah yaitu tidak tamat SD sampai dengan SD sebanyak 76,93% serta yang berpendidikan SLTP sampai SLTA sebanyak 23,03%. Dari informasi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang bergerak pada sektor ini masih relatif rendah.
Penghasilan nelayan tradisional berkisar antara Rp. 562.500 sampai Rp. 1.300.000. Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan tradisional tertinggi adalah kecamatan Mawasangka Timur yaitu Desa Lasori dengan konstribusi penghasilan rata-rata Rp. 1.300.000/bln, sedangkan Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan yang terendah adalah kecamatan Kadatua yaitu sebesar Rp. 425.000.
Jika diamati lebih jauh, ternyata yang dapat memberikan peningkatan penghasilan nelayan tradisional pada wilayah Coremmap II Kabupaten Buton adalah kombinasi mata pencaharian nelayan tradional dengan budidaya rumput laut, disusul kombinasi mata pencaharian berdagang dan bahkan pada sektor mata pencaharian alternatif budidaya rumput laut dan berdagang memberikan konstribusi yang lebih baik jika dibadingkan dengan mata pencaharian utama yaitu sebagai nelayan tradisional.
Nelayan pembudidaya adalah nelayan yang melaksanakan aktifitasnya pada sektor perikanan dalam artian, mereka melaksanakan kegiatan usaha budidaya perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya. Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada 11 kecamatan yang tersebar pada 20 Kelurahan/Desa dalam wilayah coremmap II kabupaten Buton, ternyata aktifitas nelayan pembudidaya di daerah ini terbagi dalam dua jenis komoditi budidaya yaitu komoditi rumput laut dan karamba.
Kegiatan budidaya akan memberikan konstribusi penghasilan yang baik, manakala usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk skala usaha dan manakala kegiatan budidaya dilaksanakan dalam skala kecil, maka tidak memberikan konstribusi yang signifikan bagi nelayan pembudidaya terwsebut. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya berkisar antara Rp. 582.500,- sampai Rp. 1.667.500,-. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya yang tertinggi terkonsentrasi di kecamatan Lasalimu Selatan dan terendah terkonsentrasi di kecamatan Kadatua. Rendahnya tingkat penghasilan nelayan di kecamatan Kadatua, kemungkinan disebabkan oleh; (1) rumput laut yang dibudidayakan bukan berada dalam usaha, (2) mata pencaharian alternatif (MPA) dalam hal ini memancing tidak memberikan konstribusi yang signifikan terhadap penghasilan kepala keluarga, (3) lokasi penanaman rumput laut, tidak cocok/layak untuk budidaya rumput laut, (4) tingkat sdm yang rendah.
Program coremmap II di kabupaten Buton, memberikan solusi terhadap permasalahan modal yang dihadapi oleh nelayan selama ini. Program coremmap II kabupaten Buton berkonstribusi terhadap peminjaman modal yaitu sebesar 38,10%, P2KP (4,26%), penampung (9,52%), dan PPK (4,76%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa terjadi; penigkatan penghasilan (57,14%), tetap (23,81%), dan turun (19,05%) dibandingkan dengan tahun 2007. ini sangat beralasan karena pada tahun 2008 terjadi peningkatan harga rumput laut yang sangat signifikan dibanding dengan tahun lalu. Dari tingkat penghasilan tersebut ternyata yang dipergunakan menabung sebanyak 28,57% dan digunakan untuk konsumsi dan sekolah sebesar 71,47%.
Mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir Kabupaten Buton adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian utama. kategorisasi daripada mata pencaharian alternatif adalah waktu yang dipergunakan lebih sedikit dicurahkan jika dibandingkan dengan mata pencaharian utama. Namun kadang secara tidak sadar kadang mata pencaharian alternatif ini ternayata memberikan konstribusi pendapatan yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan mata pencaharian utama.
Data hasil survei dari 11 kecamatan yang tersebar dalam 20 desa/kelurahan pada wilayah coremmap kabupaten terlihat bahwa isteri maupun anak-anak masyarakat pesisir pada wilayah coremmap II kabupaten Buton turut memberikan partisipasinya dalam rangka membantu penghasilan/pendapatan dalam keluarga. Pelibatan anak atau isteri yang paling dominan adalah pada sektor budidaya rumput laut. Pelibatan mereka ini tidak lain adalaj semata-mata menopang pendapatan/penghasilan keluarga, disamping kesibukan tersebut ternayata ada isteri mereka melaksanakan kegiatan lain seperti tenun dan usaha membuka warung yang mendatangkan penghasilan tersendiri.
Rata-rata penghasilan/pendapatan MPA yang tertinggi adalah terkonsentrasi pada nelayan modern, diikuti secara berturut-turut; nelayan pembudidaya, petani, dan nelayan tradisional. Seperti pada ulasan di atas bahwa nelayan modern mempunyai kemampuan modal investasi yang cukup, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas kegiatan usaha atau MPA, misalnya pada sektor budidaya rumput laut dan tentunya kegiatan usaha rumput laut tersbut akan lebih besar jika dibandingkan dengan; nelayan tradisional, pembudidaya, dan petani
(Data dan Informasi Coremap II Buton)
sumber: http://marufkasim.blog.com/2011/06/26/gambaran-sosial-ekomoni-masyarakat-pesisir
PENDAHULUAN
Keberhasilan Coremap salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan, potensi dan aspirasi masyarakat. Untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat diperlukan data base sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang. Di samping dapat digunakan sebagai masukan dalam mendisain program, data base aspek sosial-ekonomi terumbu karang juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Data base sosial-ekonomi ini merupakan titik awal yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program/intervensi Coremap dilakukan.
Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan Coremap Fase II. Dalam implementasi program Coremap II Kabupaten Buton yang telah dilaksanakan meliputi; penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan lain. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan di bidang sarana prasarana, pihak Coremap II telah memberikan bantuan berupa dana Block Grant pada masing-masing desa di wilayah program. Begitu pula halnya dengan pengembangan di bidang ekonomi, pihak Coremap II telah meluncurkan dana AIG dan Seed Fund. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya dengan tidak merusak lingkungan pesisir.
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Hasil analisis survei pada 11 Kecamatan Wilayah coremmap II dan tersebar pada 20 Desa/Kelurahan memperlihatkan bahwa, masyarakat yang bergerak sektor nelayan tradisional mempunyai tingkat pendidikan relatih rendah yaitu tidak tamat SD sampai dengan SD sebanyak 76,93% serta yang berpendidikan SLTP sampai SLTA sebanyak 23,03%. Dari informasi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang bergerak pada sektor ini masih relatif rendah.
Penghasilan nelayan tradisional berkisar antara Rp. 562.500 sampai Rp. 1.300.000. Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan tradisional tertinggi adalah kecamatan Mawasangka Timur yaitu Desa Lasori dengan konstribusi penghasilan rata-rata Rp. 1.300.000/bln, sedangkan Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan yang terendah adalah kecamatan Kadatua yaitu sebesar Rp. 425.000.
Jika diamati lebih jauh, ternyata yang dapat memberikan peningkatan penghasilan nelayan tradisional pada wilayah Coremmap II Kabupaten Buton adalah kombinasi mata pencaharian nelayan tradional dengan budidaya rumput laut, disusul kombinasi mata pencaharian berdagang dan bahkan pada sektor mata pencaharian alternatif budidaya rumput laut dan berdagang memberikan konstribusi yang lebih baik jika dibadingkan dengan mata pencaharian utama yaitu sebagai nelayan tradisional.
Nelayan pembudidaya adalah nelayan yang melaksanakan aktifitasnya pada sektor perikanan dalam artian, mereka melaksanakan kegiatan usaha budidaya perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya. Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada 11 kecamatan yang tersebar pada 20 Kelurahan/Desa dalam wilayah coremmap II kabupaten Buton, ternyata aktifitas nelayan pembudidaya di daerah ini terbagi dalam dua jenis komoditi budidaya yaitu komoditi rumput laut dan karamba.
Kegiatan budidaya akan memberikan konstribusi penghasilan yang baik, manakala usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk skala usaha dan manakala kegiatan budidaya dilaksanakan dalam skala kecil, maka tidak memberikan konstribusi yang signifikan bagi nelayan pembudidaya terwsebut. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya berkisar antara Rp. 582.500,- sampai Rp. 1.667.500,-. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya yang tertinggi terkonsentrasi di kecamatan Lasalimu Selatan dan terendah terkonsentrasi di kecamatan Kadatua. Rendahnya tingkat penghasilan nelayan di kecamatan Kadatua, kemungkinan disebabkan oleh; (1) rumput laut yang dibudidayakan bukan berada dalam usaha, (2) mata pencaharian alternatif (MPA) dalam hal ini memancing tidak memberikan konstribusi yang signifikan terhadap penghasilan kepala keluarga, (3) lokasi penanaman rumput laut, tidak cocok/layak untuk budidaya rumput laut, (4) tingkat sdm yang rendah.
Program coremmap II di kabupaten Buton, memberikan solusi terhadap permasalahan modal yang dihadapi oleh nelayan selama ini. Program coremmap II kabupaten Buton berkonstribusi terhadap peminjaman modal yaitu sebesar 38,10%, P2KP (4,26%), penampung (9,52%), dan PPK (4,76%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa terjadi; penigkatan penghasilan (57,14%), tetap (23,81%), dan turun (19,05%) dibandingkan dengan tahun 2007. ini sangat beralasan karena pada tahun 2008 terjadi peningkatan harga rumput laut yang sangat signifikan dibanding dengan tahun lalu. Dari tingkat penghasilan tersebut ternyata yang dipergunakan menabung sebanyak 28,57% dan digunakan untuk konsumsi dan sekolah sebesar 71,47%.
Mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir Kabupaten Buton adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian utama. kategorisasi daripada mata pencaharian alternatif adalah waktu yang dipergunakan lebih sedikit dicurahkan jika dibandingkan dengan mata pencaharian utama. Namun kadang secara tidak sadar kadang mata pencaharian alternatif ini ternayata memberikan konstribusi pendapatan yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan mata pencaharian utama.
Data hasil survei dari 11 kecamatan yang tersebar dalam 20 desa/kelurahan pada wilayah coremmap kabupaten terlihat bahwa isteri maupun anak-anak masyarakat pesisir pada wilayah coremmap II kabupaten Buton turut memberikan partisipasinya dalam rangka membantu penghasilan/pendapatan dalam keluarga. Pelibatan anak atau isteri yang paling dominan adalah pada sektor budidaya rumput laut. Pelibatan mereka ini tidak lain adalaj semata-mata menopang pendapatan/penghasilan keluarga, disamping kesibukan tersebut ternayata ada isteri mereka melaksanakan kegiatan lain seperti tenun dan usaha membuka warung yang mendatangkan penghasilan tersendiri.
Rata-rata penghasilan/pendapatan MPA yang tertinggi adalah terkonsentrasi pada nelayan modern, diikuti secara berturut-turut; nelayan pembudidaya, petani, dan nelayan tradisional. Seperti pada ulasan di atas bahwa nelayan modern mempunyai kemampuan modal investasi yang cukup, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas kegiatan usaha atau MPA, misalnya pada sektor budidaya rumput laut dan tentunya kegiatan usaha rumput laut tersbut akan lebih besar jika dibandingkan dengan; nelayan tradisional, pembudidaya, dan petani
(Data dan Informasi Coremap II Buton)
sumber: http://marufkasim.blog.com/2011/06/26/gambaran-sosial-ekomoni-masyarakat-pesisir
Konservasi Kawasan Akomodasi Kepentingan Nelayan
Jakarta,
Harian Nusantara - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan
mengakomodasi kepentingan nelayan terkait dengan upaya mengelola
sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kepentingan nelayan
tidak dikurangi dengan penerapan sistem zonasi (pemanfaatan tata ruang)
untuk kawasan konservasi demi kelestarian, kelangsungan sumber daya
ikan. “Jadi semuanya clear, nelayan ada di situ (pengelolaan kawasan
konservasi). Kita ingin alam (laut) lestari. Masyarakat, nelayan masih
boleh memanfaatkan laut, tapi dengan pengaturan,” Agus Dermawan,
Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) KKP mengatakan kepada
Harian Nusantara (3/8).

Indonesia
adalah negara
kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau. Potensi ekonomi
kelautan sangat besar, yang meliputi lahan budidaya (12,4 juta hektar),
perikanan tangkap (6,8 juta ton), cadangan minyak bumi (9,1 milyar
barel), cekungan minyak dan gas/migas sampai 70 persen. Potensi tersebut
akan memberi manfaat kalau dibarengi dengan pengembangan konservasi
sumber daya ikan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga upaya
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan mutlak
diberlakukan. “Masyarakat, termasuk LSM (lembaga swadaya masyarakat)
harus bisa membedakan pemanfaatan kawasan konservasi dan di luar
konservasi. Ada perbedaannya.”
KKP
melihat bahwa peraturan yang ada sudah memayungi inisiasi masyarakat
lokal, masyarakat adat dan tradisional dalam konteks hukum nasional.
Peraturan Menteri (Permen) No. 17/2008 sudah mengakomodasi kepentingan
masyarakat lokal. Kategori Kawasan Konservasi Maritim (KKM) terdiri dari
dua, yaitu
perlindungan adat maritim dan perlindungan budaya maritim. “Jadi
criteria, kategori tersebut dibentuk untuk melindungi kearifan lokal dan
masyarakat adat yang berlaku. Budaya maritime untuk menginisiasi
berbagai hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat. Payung hukumnya,
yaitu Undang Undang (UU No. 27 Tahun 2007) yang memberi kekuatan
pada level adat dan tradisional.”
Hal
lain yang esensial dari pengelolaan kawasan konservasi yaitu pengubahan
paradigma, dari yang lama menjadi baru. Domain kawasan konservasi
dulunya di bawah otoritas Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Paradigma
tersebut berkembang karena domain nya territorial. Sekarang,
paradigmanya harus berkembang ke domainwilayah perairan. Sehingga KKP
merasa perlu membangun kawasan konservasi yang dibarengi dengan
pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya. “Kami
berpijak pada kepentingan pengembangan ini (wilayah
perairan).”
Paradigma
lama, yang domain nya territorial rawan konflik, terutama yang terkait
dengan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir. Nelayan, ibaratnya
dikalahkan oleh kepentingan lain karena domain dan paradigmanya
berorientasi pada territorial. “Karena rejim yang lama, terbukti bahwa
nelayan kita dikalahkan.”
Sehingga
UU No. 27/2007, seketika diterbitkan, sudah mulai meninggalkan strategi
lama pengelolaan kawasan konservasi. Nelayan dan masyarakat lokal
secara turun temurun hidup dan mencari nafkah di kawasan tersebut.
Semuanya menjadi satu kawasan terpadu, dan tidakimaginary mengenai
berbagai hal terkait dengan upaya mengonservasi kawasan. “UU No. 27/2007
dan UU mengenai Perikanan (No. 31 Tahun 2004) sudah mengakomodasi dan
mengatur berbagai kepentingan nelayan sehingga tidak tubrukan dengan
kepentingan sector lain, seperti wisata bahari, perhubungan dan lain
sebagainya. Kawasan
konservasi hanya sebatas pengaturan pengelolaan yang berdasarkan kaidah
dan prinsip konservasi. Tidak ada upaya mengesampingkan kepentingan
nelayan. Jadi semuanya sudahclear.”
Masyarakat
adat yang men-declare kawasan konservasi hanya terikat dengan sanksi
hukum adat kalau memang terjadi pelanggaran. Sehingga seorang pelanggar
yang bukan berasal dari daerah yang sudah di-declaresebagai kawasan
konservasi, tidak bisa dikenakan sanksi hukum adat. Sebaliknya, pelaku
pelanggaran tersebut diberi sanksi sesuai dengan hukum nasional
Indonesia. “Misalkan pelakunya berasal dari Jakarta, dia tidak bisa
dikenakan sanksi hukum adat di kawasan yang sudah mengonservasi. Tetapi
kalau pelakunya berasal dari daerah tersebut, ada kesepakatan yang
diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini tidak
bertentangan dengan hukum nasional.”
Di
sisi lain, kawasan konservasi sempat di-declare, mencakup 10 persen
dari representasi
ekosistem esensial yaitu mangrove, terumbu karang, padang lamun.
Pemerintah menyangupi deklarasi tersebut, karena memang pernah
dibicarakan di berbagai forum internasional. Usulan dan permintaan
internasional, sesungguhnya bukan suatu masalah. Kawasan konservasi
diperluas bukan masalah bagi Pemerintah Indonesia. Tetapi (perluasan)
bukannya lebih baik, karena semakin besar kawasan konservasi, semakin
mengurangi aktivitas nelayan untuk menangkap ikan. “Logikanya, kalau
kawasan konservasi lebih besar daripada areal penangkapan ikan,
kesempatan menangkap ikan berkurang. Sehingga kajian kami, kawasan
konservasi perairan tetap harus mendukung kelestarian sumber daya
perikanan, tapi juga menjamin kepentingan nelayan, masyarakat pesisir.”
Perhitungan
usulan 10 persen dari keseluruhan luasan wilayah perairan Indonesia
yang dikonservasi, setara dengan 31 juta hektar. Karena luas keseluruhan
wilayah perairan Indonesia mencapai sekitar 310 juta
hektar. Sehingga kalau ketentuan konservasi 10 persen, berarti luas
kawasan (yang dikonservasi) menjadi sekitar 31 juta hektar. Sementara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum COP-CBD di Brazil tahun
2006 berkomitmen pada pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 20
juta hektar pada tahun 2020. “Jumlah 20 juta hektar lebih kecil
dibanding usulan 31 juta hektar. Kita masih memproses agar bisa
menjangkau (31 juta hektar). Tetapi kalau kita mau realistis, 20 juta
hektar sudah ideal untuk mendukung kelestarian sumberdaya ikan. Karena
kegiatan konservasi juga membutuhkan pendanaan, kelembagaan yang efektif
dan perekonomian rakyat, termasuk masyarakat pesisir serta nelayan.”
(Liu)
Pelajar dan Mahasiswa Bersihkan Pantai Tanjung Bira

Ikatan Pelajar Mahasiswa Bulukumba
Komisariat Bontobahari (IPMAH Bontobahari) membersihkan Pantai Tanjung
Bira, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Minggu (11/08/2013). FOTO : IPMAH
Bontobahari.
BULUKUMBA, KabarKampus—Pantai
Tanjung Bira memiliki lansekap alam yang indah. Pantai ini selalu
menjadi tujuan wisatawan domestik dan mancanegara. Namun sayang pantai
yang indah ini sering kotor akibat ulah wisatawan yang tak mau menjaga
kebersihan pantai.
Kondisi inilah yang membuat Ikatan Pelajar Mahasiswa Bulukumba
Komisariat Bontobahari atau yang biasa disingkat IPMAH Bontobahari
bekerja sama kerukunan Pelajar Mahasiswa Bira (KPMB-Bira) dan Kerukunan
Pelajar Mahasiswa Ara-Lembanna (KEPMA Ara-Lembanna), untuk membersihkan
Pantai Tanjung Bira.
Sekitar 50 orang terdiri dari pelajar dan mahasiswa melaksanakan
kegiatan yang mengusung tema “Mari Bersama Peduli Kebersihan Pantai”
pada hari Minggu, 11 Agustus 2013. Selain mengumpulkan sampah yang
berserakan mereka juga memberikan informasi kepada pengunjung untuk
turut menjaga kebersihan pantai.
Generasi muda ini pun membawa poster yang berisi ajakan memelihara Pantai Tanjung Bira.
“Untunglah
para wisatawan juga ikut terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Nirwan
Klaners, ketua panitia kegiatan. Menurut Nirwan kegiatan ini bertujuan
meningkatkan kesadaran para
wisatawan untuk menjaga kelestarian Pantai Tanjung Bira yang indah. Ia
dan rekan-rekannya berharap anugerah Tuhan berupa pantai indah di
Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba ini dapat terus
terjaga.
Pantai Tanjung Bira adalah salah satu pantai terindah yang dimiliki
Indonesia. Di pantai ini pasirnya putih berkilau. Sementara air lautnya
bening. Warga Sulawesi Selatan sering mengunjungi pantai bila musim
liburan atau hari-hari besar. Bahkan wisatawan mancanegara pun sering
terlihat menghabiskan waktunya di pantai ini.
Bagaimana kondisi wisata alam di tempat kaka? []
http://kabarkampus.com/2013/08/pelajar-dan-mahasiswa-bersihkan-pantai-tanjung-bira/
Indonesia, Salah Satu Pembunuh Hiu Terbesar di Dunia
Indonesia adalah salah satu negara penangkap ikan hiu terbesar di
dunia saat ini. Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan oleh
lembaga TRAFFIC yang melakukan pemantauan terhadap perdagangan satwa
liar dunia. Pernyataan TRAFFIC ini keluar menyusul adanya permintaan
dari Uni Eropa yang saat ini tengah menyusun upaya perlindungan bagi
tujuh spesies hiu dan manta.
Hiu yang mati setelah dipotong siripnya. Foto: Nancy Boucha
Selain Indonesia, India juga menjadi negara terbesar pembunuh hiu
secara gobal. Kedua negara ini menyumbangkan lebih dari seperlima
kebutuhan daging dan sirip hiu untuk kebutuhan ekspor. Selain kedua
negara tersebut, 18 negara lain yang juga tercatat sebagai pembunuh hiu
terbesar di dunia adalah Spanyol, Taiwan, Argentina, Mexico, Amerika
Serikat, Malaysia, Pakistan, Brasil, Jepang, Perancis, Selandia Baru,
Thailand, Portugal, Nigeria, Iran, Sri Lanka, Korea Selatan dan Yaman.
Negara-negara Uni Eropa sendiri saat ini memang tengah
menindaklanjuti hasil dari Pertemuan CITES bulan Maret silam di Bangkok,
Thailand yang mengumumkan tujuh spesies hiu dan manta yang dilindungi.
Regulasi ini akan diterapkan mulai bulan September 2014 tahun depan
untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk
menentukan sejauh apa tingkat keberlanjutanyang masih bisa ditoleransi
dalam perdagangan spesies-spesies ini dan memberikan kesempatan bagi
industri perikanan mereka untuk beradaptasi dengan regulasi baru ini.
Ikan Hiu adalah jenis satwa yang mengalami pertumbuhan lambar dan
perkembangbiakan yang jarang. Hilangnya hiu diyakini oleh para pakar
akan merusak keseimbangan ekosistem kelautan di dunia, dan menyebabkan
ledakan jumlah ubur-ubur. Beberapa jenis hiu, banyak ditangkap di
perairan secara tidak sengaja, namun melihat nilai dagang sirip dan
daging hiu, maka biasanya nelayan justru membunuhnya untuk dijual.
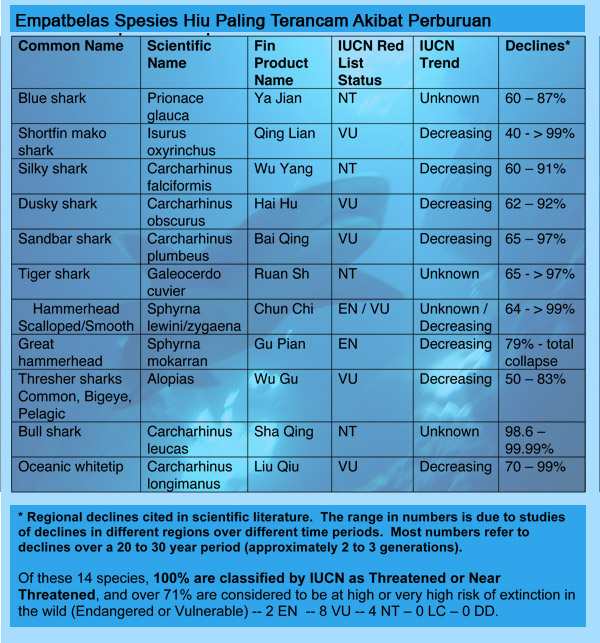
Sumber: SharkSaver
“Kunci untuk mengimplementasikan aturan CITES adalah dengan
memberikan standarisasi rantai perdagangan yang jelas untuk membantu
penegakan hukum dan melakukan verifikasi bahwa penangkapan ini adalah
sesuatu yang ilegal,” ungkap salah satu penulis laporan ini, Victoria
Mundy-Taylor.
Ketujuh spesies yang dilindungi lewat aturan CITES adalah whitetip
shark, porbeagle shark, tiga spesies hiu martil, serta dua spesies ikan
pari manta, yang semuanya sudah masuk kategori terancam di dalam Daftar
Merah IUCN. Ketujuh spesies ini masuk dalam Appendix II di dalam
peraturan CITES, dimana satwa ini masuk dalam kategori terancam akibat
perdagangan atau bisa menjadi terancam tanpa adanya kontrol dan
pengawasan yang ketat.
Penulis : Oleh Aji Wihardandi, July 31, 2013
http://www.mongabay.co.id/2013/07/31/indonesia-salah-satu-pembunuh-hiu-terbesar-di-dunia/?fanpagefb
Label:
Fauna dan Flora,
Illegal Fishing,
Konservasi,
Pelestarian
Langganan:
Komentar (Atom)

